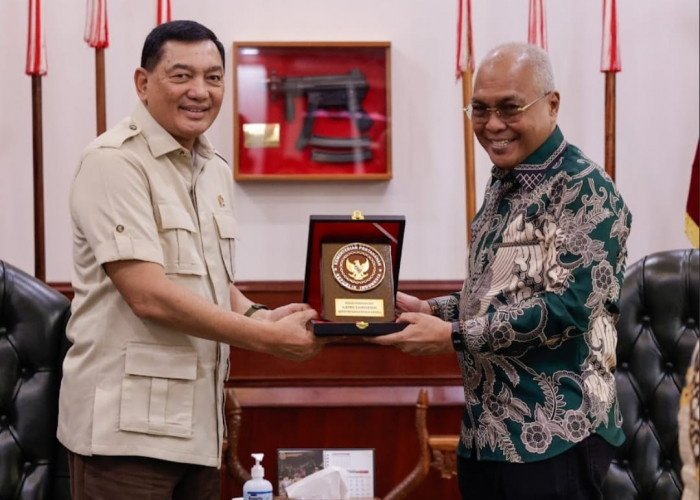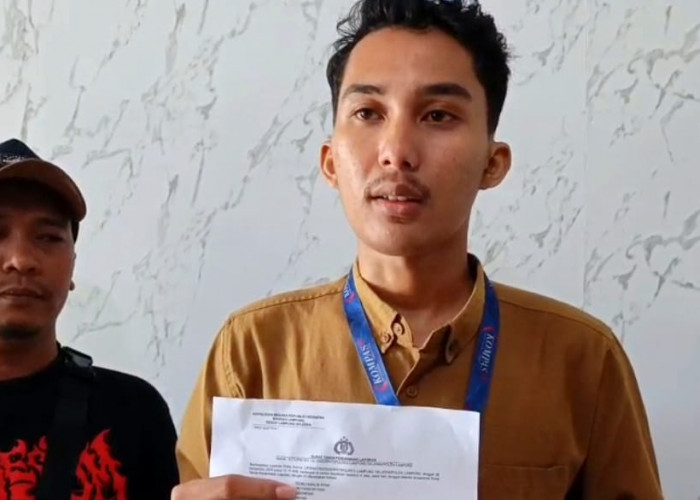Orang Media Bagaikan Katak dalam Tempurung?

--
Oleh: Wicaksono Wicaksono
Waktu muda dulu, saya pikir jadi wartawan itu pekerjaan paling berguna di dunia. Setiap pagi saya datang ke redaksi dengan semangat, merasa bahwa apa yang saya tulis bisa mengubah sesuatu. Membongkar korupsi, mengangkat suara orang kecil, atau sekadar mengingatkan pejabat bahwa ada mata yang mengawasi.
Hari-hari ini, ketika saya duduk di beranda rumah sambil menyeduh kopi, saya melihat anak-anak muda yang dulu bersama saya di ruang redaksi, satu per satu angkat kaki dari profesi ini. Ada yang jadi content creator, ada yang jualan online, dan banyak yang diam-diam menganggur. Media yang dulu seperti rumah bagi kami, kini seperti kapal tua yang lambat karam. Bukan karena tak ada awak, tapi karena nakhodanya lupa membaca arah angin.
Kita bisa saja bicara panjang lebar soal iklan digital yang direbut Meta dan Google. Bisa juga menyalahkan algoritma TikTok atau kebijakan pemerintah yang mencabut satu per satu sumber penghasilan media konvensional.
Tapi di balik semua alasan itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: kenapa media kita tidak kunjung bisa berubah?Saya pikir, ini bukan cuma soal uang atau teknologi. Ini soal cara berpikir.
Orang media terlalu sering berdiskusi dengan sesama orang media. Seminar jurnalisme, pelatihan media, konferensi pers, semuanya hanya mengulang-ulang suara dari dalam sumur yang sama.
Orang media hidup seperti katak dalam tempurung, saling menyahut tanpa pernah benar-benar keluar dan bertanya ke dunia luar. Padahal jawaban mungkin ada di luar sana, di ruang-ruang tempat orang teknologi membicarakan masa depan interaksi, di meja-meja rapat para pebisnis yang sedang memikirkan cara baru menjual kepercayaan, atau di komunitas startup yang sedang mengubah cara manusia mengakses informasi.
Ketika pekerja media sibuk menyelamatkan etika jurnalisme, dunia sudah beranjak ke fase ketika kepercayaan tidak ditentukan oleh etika, tapi oleh relevansi dan kedekatan.
Dulu, orang mencari berita karena ingin tahu. Sekarang, mereka mencari karena ingin merasa. Merasa dilihat, merasa dimengerti, merasa terhubung. Ketika media bicara soal “melawan hoaks”, platform seperti TikTok menawarkan sesuatu yang lebih sederhana dan memikat: cerita manusia.
Pekerja media bicara tentang kredibilitas, mereka bicara tentang kedekatan. Media sibuk menjaga independensi redaksi, kreator sibuk membuat konten yang bisa bikin orang terhenti sejenak di tengah scroll tanpa henti.
Saya tidak sedang meremehkan nilai-nilai jurnalistik. Justru sebaliknya. Saya percaya etika, akurasi, dan keberimbangan tetap penting. Tapi nilai-nilai itu hanya akan hidup kalau bisa dibungkus dalam cara baru yang dipahami generasi sekarang.
Menurut hemat saya, media tidak bisa terus-terusan menyajikan kebenaran dalam format usang dan berharap penontonnya tetap setia. Dunia sudah terlalu cepat bergerak. Orang lebih percaya pada satu video testimoni di WhatsApp daripada lima halaman laporan investigatif. Bukan karena mereka bodoh. Tapi karena media konvensional gagal menjelaskan dengan cara yang menyentuh.
Kondisi inilah yang tidak kunjung disadari oleh banyak pengelola media. Mereka mengira krisis ini bisa diselesaikan dengan menambah jumlah berita, mempercepat waktu tayang, atau memperluas kanal distribusi. Padahal persoalannya bukan kuantitas. Yang mereka hadapi adalah krisis makna.
Berita tidak lagi mengandung nilai karena wartawan tidak lagi punya waktu, tenaga, atau keberanian untuk menciptakan kedalaman. Di ruang redaksi hari ini, yang dihitung bukan lagi nilai jurnalistik, tapi potensi klik. Editor tidak lagi bertanya “apa makna cerita ini?”, tapi “berapa engagement-nya di Instagram?”.
Sumber: